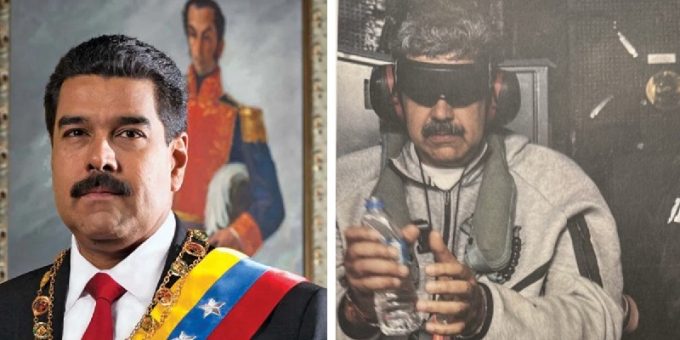Adrian Nalendra Perwira
Peneliti Ekonomi GREAT Institute
“Seandainya negeriku serupa rahim ibu; merawat kehidupan menguatkan yang rapuh”
Akhir-akhir ini, penggalan bait dari tembang “Seperti Rahim Ibu” milik grup musik legendaris Efek Rumah Kaca kerap terdengar kembali. Betapa tidak, metafora dalam liriknya beresonansi dengan batin banyak masyarakat sipil yang mendambakan perlindungan—paling tidak untuk bersuara, dan bekerja.
Demonstrasi di akhir Agustus masih menyisakan luka, tetapi dari luka itu tumbuh tekad bersama untuk Indonesia yang lebih adil. Suara masyarakat sipil, kampus, dan lembaga riset menggema: ekonomi tidak cukup sekadar tumbuh—ia harus menyejahterakan. Di lapangan, kegelisahan terasa nyata. Kualitas kerja yang rapuh, gelombang PHK, ketimpangan yang menahun, serta pekerjaan informal yang masih minim perlindungan. Di sinilah relevansi ukuran kebijakan: kita butuh target yang dapat meningkatkan kualitas kerja.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, ada indikator baru yang jarang dibahas tetapi sebenarnya menarik untuk kita amati: proporsi penciptaan lapangan kerja formal yang angkanya ditarget sebesar 37,95 persen. Disebutkan dalam dokumen tersebut, indikator proporsi penciptaan lapangan kerja formal merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja; makin tinggi persentasenya, makin positif perkembangan dalam pasar tenaga kerja.
Sayangnya, tak dijabarkan secara rinci apa yang dihitung oleh indikator tersebut. Rasanya, tidak mungkin jika ia merupakan target stok pangsa pekerja formal—mustahil pemerintah ingin menurunkan pangsa dari 40,60 persen per Februari 2025 ke 37,95 persen di 2026. Juga kecil kemungkinan jika angka tersebut merupakan persentase peningkatan dari pangsa pekerja formal yang berarti proporsi pekerja formal menjadi 55,86 persen pada 2026—mengingat selama satu dekade terakhir proporsi sektor formal-informal tak banyak berubah.
Dus, tulisan ini menginterpretasikan jika angka 37,95 persen merupakan indikator arus (flow)—porsi pekerjaan baru yang berstatus formal pada 2026. Pangsa pekerja formal naik hanya jika arus masuk ke pekerjaan formal (perekrutan pekerjaan formal dan/atau transisi pekerja yang masuk ke sektor formal) lebih besar daripada arus keluarnya (PHK dalam sektor formal dan/atau lebih banyak pekerja yang masuk ke sektor formal daripada keluar). Pertanyaan yang perlu kita utarakan adalah mengapa pemerintah perlu mengenalkan indikator baru ini? Apakah angka yang ditetapkan di sini realistis? Bagaimana kita bisa mencapai target ini?
Kondisi saat ini
Per Februari 2025, penduduk bekerja mencapai 145,77 juta, naik 3,59 juta dibanding Februari 2024. Pada saat yang sama, proporsi pekerja informal naik dari 59,17 persen ke 59,40 persen, sehingga pangsa formal turun dari 40,83 persen ke 40,60 persen (meski jumlah pekerja formal tetap bertambah).
Dari rilis BPS, jumlah pekerja formal per Februari 2025 sebesar 59,19 juta. Dengan basis ini, kenaikan bersih pekerja formal dalam setahun terakhir mencapai 1,13 juta, alias sekitar 31,47 persen dari tambahan bersih pekerjaan. Artinya, selama 2024–2025, “tambahan porsi formal” berada di kisaran 31,47 persen.
Jika indikator RAPBN 2026 kita baca sebagai porsi pekerjaan baru yang formal, maka target 37,95 persen berarti pemerintah menargetkan kenaikan sekitar 6,48 poin persentase dibanding realisasi bersih tahun lalu. Dengan asumsi tambahan orang bekerja setahun ke depan tidak berbeda dengan tahun lalu (3,59 juta), target 37,95 persen setara sekitar 1,36 juta pekerja formal bersih; ada selisih sekitar 233 ribu yang perlu ditutup. Target yang masih terbilang realistis namun tetap perlu kerja serius untuk mencapainya.
Putar Balik dari Omnibus Law?
Secara kelembagaan, ada indikasi indikator baru ini berbeda arah dari Omnibus Law terhadap Penciptaan Kerja (UU Cipta Kerja) yang pertama disahkan pada Oktober 2020 sebagai UU No. 11 Tahun 2020. Literatur menunjukkan jika sejumlah perubahan dalam UU Cipta Kerja memang mengurangi perlindungan pekerjademi fleksibilitas pasar tenaga kerja, sekaligus mereposisikan norma ketenagakerjaan dari level undang-undang ke regulasi eksekutif yang berpotensi mempermudah pengurangan perlindungan di masa depan.
Menurut studi Mahy (2021), UU ini menghilangkan atau mengurangi beberapa perlindungan ketenagakerjaan dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan outsourcing, penetapan upah, PHK, pesangon, cuti, waktu kerja, dan lainnya. Di sisi dampak sektoral, studi Sanders dkk. (2024) mengidentifikasi amandemen yang mengurangi “safeguards” bagi lingkungan serta hak pekerja/petani, dengan risiko perluasan pekerjaan berupah rendah dan prekariat.
Sementara itu, studi ILO (2025) pada sektor garmen menunjukkan pasca-UU terjadi perluasan penggunaan PKWT ketimbang perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sulitnya akses JKP bagi pekerja PKWT, dan bahkan kebijakan upah layak terdorong mundur—menggambarkan bagaimana fleksibilitas dapat menipiskan kualitas/formalitas kerja bila tidak diimbangi pagar mutu.
Dalam dokumen RAPBN 2026 disebutkan jika pekerjaan formal memberikan jaminan pendapatan, stabilitas kerja, serta manfaat-manfaat tambahan seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dll. Pernyataan ini agak ironis karena meskipun secara konseptual benar, pekerjaan formal di Indonesia tak serta-merta menyertakan hal di atas.
BPS mengklasifikasikan pekerja formal di Indonesia berdasarkan status pekerjaan utama. Tenaga kerja yang berstatus “buruh/karyawan/pegawai” atau “berusaha dibantu buruh tetap” diklasifikasikan sebagai pekerja formal. Pangsa pekerja formal saat ini sebesar 40,60 persen dari total tenaga kerja. Namun, menurut ILO (2018) jika dilihat dari sisi perlindungan sosialnya, sebenarnya tenaga kerja informal di Indonesia bisa mencapai 85 persen.
Artinya, tidak semua pekerja yang diklasifikasikan formal menurut BPS memiliki akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan sesuai kriteria ILO—yakni iuran jaminan sosial yang dibayar pemberi kerja (idealnya pensiun), atau hak atas cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar.
Karena itu, agar manfaat dari pekerjaan formal seperti yang dijanjikan RAPBN benar-benar terasa, tidak cukup menaikkan porsinya saja; mutunya—dan metrik pengukurannya—juga harus diperbaiki.
Potensi Bonus Demografi
Lantas, di mana pemerintah harus meletakkan fokus? Mendorong formalisasi usaha ultra-mikro dalam horizon singkat jelas sulit; jalan tercepat menaikkan arus formal adalah mengalirkan lulusan muda terdidik ke kantong kerja formal dan menjaga retensinya. Nampaknya, Generasi Z menjadi harapan utama pemerintah untuk menaikkan proporsi lapangan kerja formal.
Studi Pratomo dan Manning (2022) serta Sugiharti dkk. (2022) menawarkan bukti yang senada: ekspansi sektor formal di Indonesia berkorelasi erat dengan tumbuhnya generasi muda terdidik yang masuk ke pasar tenaga kerja, sementara mobilitas dari informal ke formal ada tetapi relatif lebih kecil kemungkinannya; pekerja yang lebih tua juga lebih sulit masuk ke sektor formal.
Menurut Pratomo dan Manning (2022), tenaga kerja usia muda dan berpendidikan tinggi memiliki mobilitas yang lebih tinggi daripada kelompok usia lain dan kelompok dengan pendidikan lebih rendah. Gen Z adalah generasi terbesar: 27,94 persen penduduk (Sensus Penduduk 2020).
Di pasar tenaga kerja, angkatan kerja 15–24 tahun diproyeksikan sekitar 21,77 juta orang pada 2025 dan tetap di kisaran 21,1 juta pada 2029; sementara kelompok usia 25–29 tahun (yang menampung “Gen Z tua” dan milenial muda) sekitar 17,45 juta pada 2025 dan relatif stabil sampai 2029. Data ini menunjukkan pipeline tenaga kerja muda besar dan persisten di beberapa tahun ke depan—sebuah peluang bila lowongan formal tersedia.
Pada Februari 2025, TPT nasional 4,76 persen, tetapi di kelompok usia 15–24 tahun mencapai 16,16 persen—hampir tiga kali lipat. Ini tanda pintu masuk ke pasar kerja belum mulus: lowongan tingkat pemula masih kurang atau tidak pas dengan lulusan baru.
Pada akhirnya, target 37,95 persen proporsi penciptaan lapangan kerja formal patut diapresiasi. Namun, ia harus selaras dengan bonus demografi. Beberapa hal dapat dilakukan untuk memastikan arahnya tepat: tambah kursi kerja entry-level di sektor formal, dan sediakan penyangga agar yang sudah masuk formal tidak cepat jatuh lagi ke informal saat kontraknya habis—misalnya magang yang wajib berujung kontrak, insentif konversi PKWT ke tetap, serta bantuan iuran BPJS di 12 bulan pertama. Harapannya pemerintah mampu meraih target ini agar selangkah demi selangkah kita berjalan menuju pertumbuhan yang merawat kehidupan seraya menguatkan yang rapuh.