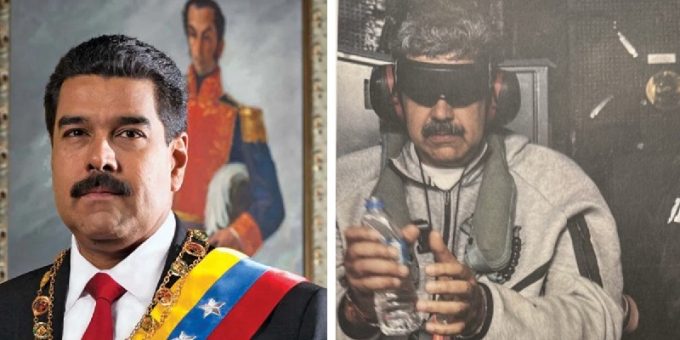Perdana Wahyu Santosa Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, dan Direktur Riset GREAT Institute EVALUASI terhadap kinerja pemerintahan selalu menjadi arena tarik-menarik antara persepsi publik, data empiris, dan framing media. Laporan “Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang dirilis oleh CELIOS pada Oktober 2025 memicu perbincangan seru di ruang publik.
Sebagian menilainya sebagai bentuk kontrol demokrasi yang sehat; sebagian lain menganggapnya terlalu pesimistis dan minim konteks ekonomi makro yang sebenarnya menunjukkan tren stabil. Kedua pandangan ini sama-sama penting, sebab demokrasi Indonesia yang dewasa dan matang membutuhkan dialektika solid antara pengawasan dan keadilan analisis.
Tantangannya adalah membedakan antara kritik berbasis data dan penilaian yang lahir dari persepsi—antara realitas empiris dan narasi yang terbentuk oleh opini kolektif. Metodologi yang Mengundang Tanya CELIOS menggunakan dua pendekatan: survei expert judgment berbasis jurnalis (120 responden dari 60 lembaga pers) dan survei nasional terhadap 1.338 responden publik. Metode ini sah dalam ranah perception study, namun bukan ukuran kinerja objektif secara ekonomi atau administratif. Jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses informasi dan sensitivitas terhadap isu publik.
Namun, profesi mereka juga hidup di medan opini—terbiasa menilai berdasarkan dinamika wacana yang cepat, bukan proses kebijakan yang kompleks dan panjang. Akibatnya, bias persepsi mudah muncul. Dalam ilmu kebijakan publik, ini disebut availability heuristic bias—penilaian yang dipengaruhi oleh informasi paling mudah diakses dan paling sering disorot media, bukan oleh data paling akurat.
Dengan demikian, hasil survei yang menempatkan rata-rata kinerja pemerintahan di angka 3 dari 10 tidak serta merta menunjukkan kegagalan struktural yang mendasar. Hasil evaluasi tersebut lebih menggambarkan kekecewaan publik terhadap ekspektasi yang belum terwujud dalam waktu singkat. Evaluasi semacam ini penting, namun perlu diimbangi dengan pembacaan data faktual agar tidak jatuh pada kesimpulan prematur.
Stabilitas di Tengah Transisi Secara ekonomi, tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran berlangsung dalam fase transisi kebijakan. Tantangan utama datang dari pelemahan ekspor akibat perlambatan ekonomi Tiongkok dan tekanan geopolitik di Timur Tengah yang menaikkan harga energi global.
Namun, indikator makro menunjukkan stabilitas relatif: pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 masih bertahan di kisaran 5,12 persen (BPS), inflasi terjaga di bawah 3 persen, dan nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil di kisaran Rp15.800–Rp16.200 per dolar AS.
Investasi asing langsung (FDI) tumbuh moderat di sektor logam dasar, kendaraan listrik, dan infrastruktur digital, meskipun belum sesuai target ambisius pemerintah. Kebijakan hilirisasi dan penguatan industri strategis menunjukkan arah keberlanjutan jangka menengah, meski dampak ekonominya belum terasa dalam setahun. Artinya, jika evaluasi dilakukan dengan kacamata makroekonomi, kinerja pemerintah tentunya tidak seburuk angka “3 dari 10”. Namun dari sisi komunikasi publik dan persepsi sosial, tampak ada kesenjangan antara narasi keberhasilan pemerintah dan pengalaman riil masyarakat dalam menghadapi tekanan harga pangan, pajak, serta daya beli yang stagnan.
Dimensi Sosial dan Politik Di ranah sosial politik, laporan CELIOS juga menyoroti persepsi publik terhadap pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan: 63 persen responden setuju bahwa corak kekuasaan semakin tersentralisasi. Persepsi ini tidak lepas dari latar belakang Presiden Prabowo sebagai purnawirawan jenderal dan kecenderungan konsolidasi kekuasaan di lingkar eksekutif. Namun, penting dicatat bahwa persepsi militeristik tidak identik dengan kemunduran demokrasi.
Dalam konteks Indonesia, command style leadership sering dipersepsikan negatif, padahal dalam fase stabilisasi politik, gaya kepemimpinan yang tegas justru bisa menjadi faktor konsolidasi kebijakan lintas kementerian. Masalah sebenarnya bukan pada gaya kepemimpinan, melainkan pada ruang partisipasi publik dalam pemerintahan yang belum optimal.
Di sinilah evaluasi menjadi relevan: publik merasa belum dilibatkan cukup dalam perumusan kebijakan strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), transisi energi hijau, dan reformasi pajak. Ini sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat kanal partisipatif dan transparansi data agar legitimasi kebijakan tidak bergantung pada popularitas semata.
Komunikasi Kebijakan Salah satu temuan paling krusial dari laporan CELIOS adalah lemahnya komunikasi kebijakan. Sebanyak 63 persen responden menilai komunikasi pemerintah “sangat buruk”. Kritik keras ini agaknya sulit disangkal. Pemerintah kerap menyampaikan program besar—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, reformasi pajak, atau program ketahanan pangan—tanpa strategi komunikasi yang menyentuh realitas masyarakat bawah.
Dalam teori kebijakan publik, komunikasi kebijakan bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi proses membangun makna bersama antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat. Ketika kebijakan gagal dipahami, resistensi sosial akan meningkat, bahkan terhadap program yang sebenarnya bernilai positif sekalipun. Dengan kata lain, masalah bukan hanya pada isi kebijakan, tetapi pada cara pemerintah mengartikulasikan niat baiknya kepada publik.
Antara Evaluasi dan Delegitimasi
Laporan kembaga kajian memang memberi ruang bagi kritik substantif, namun risko muncul ketika hasil survei semacam ini dibaca di luar konteks. Jika angka-angka persepsi digunakan sebagai bukti empiris tunggal untuk menilai performa ekonomi dan politik, maka riset berubah fungsi: dari alat koreksi menjadi instrumen delegitimasi. Objektivitas riset kebijakan menuntut penggunaan triangulasi data—menggabungkan persepsi publik, indikator ekonomi, serta evaluasi administratif internal pemerintah. Tanpa itu, riset publik berisiko memperkuat confirmation bias masyarakat, maka siapa yang sudah skeptis akan makin yakin bahwa pemerintah gagal, sementara yang pro-pemerintah akan menolak mentah-mentah hasilnya.
Oleh karena itu, baik lembaga riset maupun pemerintah perlu berkomitmen pada keterbukaan data. Lembaga kajian bisa memperluas metodologi dengan melibatkan akademisi lintas disiplin dan indikator makro, sementara pemerintah perlu menanggapinya secara konstruktif, bukan defensif. Demokrasi yang sehat bukan yang bebas kritik tentunya, melainkan juga yang mampu mengubah kritik menjadi kebijakan yang lebih baik. Penutup Evaluasi satu tahun pemerintahan adalah sekadar cermin awal, bukan vonis akhir tentunya. Kritik keras dari publik versi CELIOS ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki aspek komunikasi, koordinasi, dan tata kelolanya.
Namun, publik juga perlu menyadari bahwa reformasi struktural tidak dapat diukur dengan skala kepuasan jangka pendek. Persepsi publik memang penting, tetapi kebenaran kebijakan akan ditentukan oleh hasil nyata di lapangan: misalnya apakah kemiskinan dan pengangguran menurun, investasi produktif meningkat, dan layanan publik membaik. Itulah ukuran objektif yang perlu dijadikan dasar dalam menilai pemerintahan. Di tengah arus polarisasi opini, kebijaksanaan terbesar justru terletak pada kemampuan bangsa ini menyeimbangkan dua hal: kritik tajam dan analisis objektif. Hanya dengan keseimbangan itu, demokrasi Indonesia dapat tumbuh bukan sebagai panggung sentimen, melainkan sebagai ruang rasionalitas publik yang menghargai data, kinerja, dan harapan masa depan.