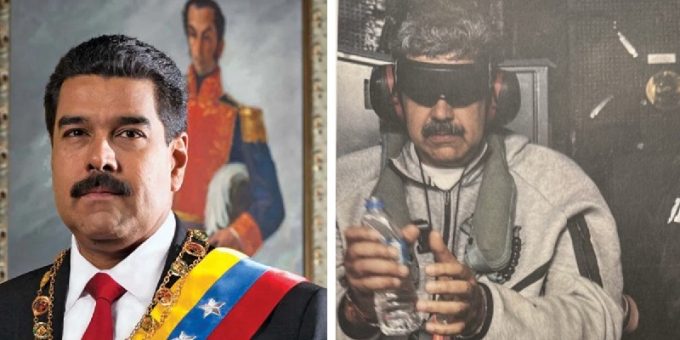Oleh : Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH.co– Data ekonomi terbaru menyodorkan pesan yang (sedikit) kurang romantis tapi sangat nyata yaitu Indonesia ingin segera “lari cepat” dan keluar dari middle-income trap, namun “otot fiskal” kita masih relatif kecil. Ini bukan sekadar debat teknokratis tentang angka namun ini soal kapasitas negara membiayai lompatan produktivitas.
Middle-Income Trap: Bukan Kutukan, Tapi Tertundanya Naik Kelas
World Bank menegaskan banyak negara pendapatan menengah berhenti naik kelas: sejak 1970, pendapatan per kapita negara menengah “median” tak pernah melampaui 10% level AS; dan hanya sebagian kecil yang berhasil naik ke status high-income sejak 1990-an.
Mengapa macet? Karena transisi dari “tumbuh lewat tenaga murah dan investasi dasar” menuju “tumbuh lewat inovasi, kualitas institusi, dan produktivitas tinggi” menuntut belanja publik yang tepat sasaran dan konsisten. Dalam bahasa yang lebih membumi: jalan tol saja tidak cukup; Anda butuh sekolah yang kompeten, riset yang hidup, layanan kesehatan yang membuat pekerja produktif, birokrasi yang tidak menghambat, dan perlindungan sosial yang mencegah guncangan membuat rumah tangga jatuh miskin.
Di titik ini, estimasi data ekonomi (World Bank) menjadi semacam rontgen: tax ratio Indonesia sekitar ~10% PDB (2000–2024) dan belanja negara sekitar ~15% PDB, sementara contoh negara yang keluar dari jebakan (Korea Selatan, Chile) menunjukkan ruang fiskal yang lebih “lega” pada fase-fase krusial pembangunan. Intinya sederhana: negara yang mau naik kelas biasanya punya kapasitas fiskal untuk membayar biaya naik kelas.
Masalah Basis, Kepatuhan, dan Kualitas Belanja
Godaan terbesar adalah menyederhanakan diagnosis yang paling gampang adalah “tinggal naikkan pajak.” Itu asumsi yang terlalu pendek kakinya. Justru yang terjadi biasanya kombinasi tiga hal:
-Pertama, basis pajak yang sempit—bukan hanya karena tarif, melainkan struktur ekonomi (informalitas), pengecualian, insentif yang menumpuk, serta tax gap (potensi yang hilang karena kepatuhan dan desain). Tanpa perlu berdebat definisi, bandingkan saja “napas fiskal” Korea: OECD mencatat tax-to-GDP Korea naik dari 20,9% (2000) ke 28,9% (2023). Ini memberi ruang bagi investasi negara pada manusia, teknologi, dan institusi.
-Kedua, administrasi dan kepatuhan. Peningkatan penerimaan yang sehat jarang datang dari “menaikkan tarif”; biasanya datang dari memperlebar jaring—data yang terintegrasi, penegakan yang adil, proses yang sederhana, serta kepastian hukum. Negara yang berhasil keluar jebakan cenderung memperkuat kemampuan mengubah pertumbuhan menjadi penerimaan—tanpa membunuh sektor produktif.
-Ketiga, kualitas belanja. Bahkan jika penerimaan naik, tanpa belanja yang efektif, hasilnya hanya “APBN lebih besar” bukan “ekonomi lebih produktif.” World Bank WDR 2024 menekankan strategi bertahap—investment, infusion, innovation—yang intinya memaksa negara menata ulang prioritas belanja agar produktivitas benar-benar naik.
Rekomendasi Strategis
Kalau targetnya serius keluar jebakan, sebaiknya resepnya harus dua sisi: menambah ruang fiskal dan mengubah kualitas pengeluaran. Ini paket yang lebih realistis dan minim ilusi:
(a) Reform penerimaan berbasis “perluasan”, bukan “pemerasan”. Fokus pada penutupan celah PPN/VAT (rasionalisasi pengecualian), penguatan pajak konsumsi tertentu (cukai yang pro-kesehatan dan pro-produktivitas), serta pajak properti yang lebih kuat di level daerah—karena itu relatif growth-friendly dibanding membebani investasi produktif.
(b) “Kontrak fiskal” yang membuat publik mau patuh. Kepatuhan naik jika warga dan dunia usaha melihat uangnya kembali sebagai layanan publik yang nyata: pendidikan vokasi yang nyambung industri, layanan kesehatan yang mengurangi kehilangan jam kerja, dan infrastruktur yang memangkas biaya logistik.
(c) Belanja negara dipaksa jadi mesin produktivitas. Naik kelas butuh belanja yang memicu human capital dan inovasi: kualitas guru, riset terapan, ekosistem industri bernilai tambah, digitalisasi layanan publik, serta perlindungan sosial yang mencegah rumah tangga “jatuh-bangun” saat shock.
(d) Disiplin evaluasi program: hentikan belanja yang tidak punya measurable outcome. Negara maju itu bukan negara yang “banyak program”, tapi negara yang berani mematikan program yang tidak berdampak.
(e) Sinkron pusat–daerah. Jika pajak dan layanan publik “terpisah”, hasilnya fragmentasi: penerimaan sulit naik, belanja tidak fokus, dan investor mendapat biaya koordinasi yang mahal.
(f) Narasi industrial policy yang waras. Bukan proteksionisme emosional, melainkan strategi upgrading: dorong ekspor bernilai tambah, perkuat rantai pasok, dan perbaiki iklim persaingan. Literatur jebakan pendapatan menengah juga menekankan structural transformation—pergeseran dari aktivitas produktivitas rendah ke tinggi sebagai kunci lolos jebakan.
Kesimpulan
Dari data Bappenas, bisa dimaknai sebagai “alarm.” Tetapi alarm itu tidak berarti “pajak harus dinaikkan.” Alarm itu berarti Indonesia perlu memperbesar kapasitas fiskal melalui perluasan basis dan kepatuhan, sambil memaksa belanja menjadi mesin yang lebih produktif. Keluar dari middle-income trap bukan soal mimpi besar bagi Indonesia; itu hanya soal APBN yang cukup kuat dan cukup cerdas untuk membayar biaya naik kelas. [ ]
*Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, dan Direktur Riset GREAT Institute