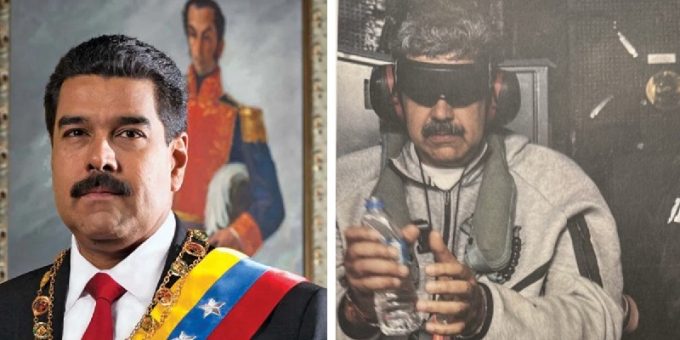Oleh: Adrian N. Perwira – Peneliti Ekonomi GREAT Institute
Dimuat di Kontan, 1 September 2025
Pemerintah menyatakan tidak akan mengenakan pajak baru atau menaikkan tarif pajak pada tahun 2026. Padahal, target penerimaan pajak pemerintah terbilang ambisius dalam RAPBN 2026: naik 13 persen dari 2.387 triliun dibanding outlook 2025. Secara rinci, PPh ditarget naik 15 persen dan PPn plus PPnBM 12 persen, berturut-turut, dari outlook 2025. Artinya, tanpa pajak dan tarif baru, strategi utamanya adalah ekstensifikasi basis dan peningkatan kepatuhan pajak.
Menteri Keuangan menyebut shadow economy sebagai salah satu ruang yang akan ditertibkan untuk mencapai target ini. Secara khusus, ia mengatakan akan fokus pada perdagangan eceran, makanan dan minuman, emas, dan perikanan. Masyarakat bertanya-tanya mengapa pedagang eceran masih harus diburu juga di tengah ekonomi yang tidak tentu.
Memahami Shadow Economy
Dalam literatur, definisi shadow economy sejatinya belum baku. OECD mengartikan shadow economy sebagai non-observed economy (NOE) yang terdiri dari tiga komponen: ekonomi underground (kegiatan yang legal tapi disembunyikan dari otoritas), ekonomi informal (produksi di luar pencatatan karena skala ekonomi atau biaya patuh), dan ekonomi ilegal (kegiatan kriminal).
Friedrich Schneider, ekonom Jerman yang mula-mula memopulerkan istilah ini, memilih menggunakan komponen ekonomi underground saja untuk mengukur shadow economy dan tidak menyertakan komponen ekonomi informal dan ilegal seperti OECD (Feige, 2016).
Dalam ceramahnya, ekonom Italia Vito Tanzi pernah mengatakan bahwa lebih bijak untuk tidak mencampur-adukkan fenomena shadow economy dan ekonomi informal karena akar penyebabnya berbeda. Tulisan ini juga memilih untuk memisahkan kedua fenomena tersebut meskipun secara teknis memang saling berkelindan.
Menurut Tanzi, ada empat penyebab terjadinya shadow economy: (1) penghindaran pajak melalui aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan atau dilaporkan “di bawah tanah”; (2) penghindaran terhadap aturan main pemerintah seperti upah minimum, keselamatan kerja, jaminan sosial, maupun jam kerja; (3) pasar ilegal yang dilarang seperti prostitusi, jual-beli obat-obatan terlarang, judi online; serta (4) praktik korupsi, baik dalam bentuk suap untuk menghindari kewajiban formal maupun penerimaan ilegal pejabat yang tidak tercatat dalam sistem resmi.
Keempat aktivitas ini menggerus basis penerimaan. Akibatnya, kualitas barang dan jasa publik juga akan merosot dan kian mendorong pelaku usaha semakin menjauhi ekonomi yang “resmi” sehingga tercipta lingkaran setan.
Dalam kerangka ILO, “informal” adalah aktivitas/pekerjaan yang tidak atau kurang tercakup aturan formal—umumnya karena skala, biaya, dan hambatan administratif. Maka dari itu, definisi menjadi penting: kalau shadow economy dipakai semakna dengan underground economy, maka fokusnya adalah pada penegakan berbasis data pada simpul bernilai besar.
Usaha memutus “lingkaran setan” ini patut didukung. Studi Lukman dan Kartiasih (2025) mengukur shadow economy di 34 provinsi di Indonesia dan menunjukkan rata-rata lintas provinsi sekitar 14,6 persen dari PDRB. Artinya, memang ada urgensi untuk penertibannya agar menjadi dorongan penambah penerimaan negara.
Meskipun demikian, kita harus waspada dengan apa yang dimaksud pemerintah saat menggunakan istilah shadow economy. Dilihat dari sektor prioritas: perdagangan eceran, makanan-minuman, emas, dan perikanan, ada potensi pencampuran fenomena: perdagangan eceran dan makanan-minuman didominasi informal pada level mikro, emas utamanya underground karena bernilai tinggi dan ada kemungkinan under-reporting, sementara perikanan bercampur informal (nelayan kecil) dan ilegal. Implikasinya sederhana: jangan jadikan pelaku informal mikro sebagai “quick win”; fokuskan penegakan pada underground bernilai besar.
Perihal Sektor Informal
Dalam satu dekade terakhir, proporsi sektor informal di Indonesia nyaris tak bergeming. Per Februari 2025, angka totalnya mencapai 59,4 persen. Menurut ILO, pekerja pada sektor informal memiliki karakteristik berpendapatan rendah, rentan miskin, dan tidak terjamah program jaminan sosial. Lambatnya proses formalisasi di Indonesia berkenaan dengan timpangnya pertumbuhan lapangan kerja, mengingat mayoritas pekerja informal berpendidikan rendah.
Bukti mikro menunjukkan banyak pelaku informal beroperasi dalam skala yang membuat biaya kepatuhan melampaui manfaat; bagi mereka, formalitas sering tidak “worth it”. Tulisan ini tidak sedang meromantisasi sektor informal. Banyak studi yang menunjukkan jika besarnya sektor informal di suatu negara berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajaknya.
Namun, agaknya kita perlu melihat sektor informal bukan sebagai pilihan yang diambil dalam penuh keleluasaan dan rasionalitas semata; ia merupakan konsekuensi struktural seperti mismatch keterampilan, lapangan kerja yang kurang inklusif, serta biaya kepatuhan yang melampaui manfaat. Lantaran itu, penertiban shadow economy harus dimaknai sebagai penegakan pada ekonomi underground bernilai besar.
Pertama,pemerintah harus mengeksekusi compliance improvement program (CIP) khusus dengan analisis intelijen dan sinergi data lintas sumber untuk memetakan pangsa dan posisi pelaku usaha berisiko tinggi di sektor prioritas. Kedua, percepat simplifikasi kepatuhan reformasi pajak yang lebih adaptif agar pelaku yang selama ini “berbayang” karena regulasi atau prosedur berbiaya tinggi beralih ke jalur formal.
Ketiga, pada segmen menengah-besar gunakan pemotongan atau pemungutan melalui platform (pemungut PPN PMSE dan PPh 22 e-commerce) di simpul bernilai tinggi untuk menekan under-reporting tanpa memburu mikro. Keempat, untuk area yang bersinggungan dengan pelarangan dan korupsi (misalnya illegal fishing, penyelundupan/rekayasa dokumen emas), prioritaskan penegakan non-pajak (KKP/Bea Cukai/PPATK).
Terakhir, pemerintah perlu umumkan “pagar keadilan” (misalnya ambang PKP PP atau pengecualian pelapak kecil dalam pemotongan platform) agar ekstensifikasi tidak berubah menjadi razia pedagang kecil. Dengan langkah-langkah ini, target 2026 dikejar tanpa membebani sektor informal yang bertahan hidup alih-alih mengakumulasi kekayaan.