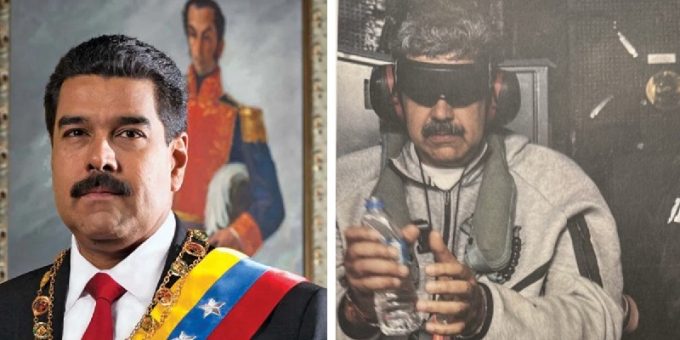Oleh Adrian N. Perwira – Peneliti Ekonomi Great Institute
Dimuat di Kompas, 28 Agustus 2025
Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan RAPBN 2026 dengan defisit 2,5% PDB dan menargetkan APBN seimbang pada 2027 atau 2028. Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 juga mematok rasio utang 2026 sekitar 40% PDB dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Pada 2024, rasio utang sendiri telah mencapai 39,2% PDB (Rp8.680 triliun) dan diperkirakan 41,2% pada 2025 (asumsi pertumbuhan 5,1% dan defisit 2,8%). Pasca-pandemi, rasio utang bergeser ke rezim baru meningkat sebesar 9persen poin di atas level pra-pandemi dan sejak itu stabil tinggi (39–41%). Memang, angka rasio utang masih jauh di bawah batas 60% PDB sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun bukan berarti tanpa risiko.
Sinyal pertama datang dari beban bunga. Hingga akhir 2025, anggaran pembayaran bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp552,1 triliun; sebesar 15,6% dari outlook belanja negara dan 19,3% dari pendapatan negara. Artinya, sebelum bicara mengenai pendanaan program prioritas, beban bunga sudah mengambil porsi yang tidak kecil. Hampir satu dari lima rupiah pendapatan negara sudah tersita untuk membayar bunga.
Komposisi portofolio kita relatif menenangkan di satu sisi: sekitar 88,12% berbentuk SBN dan mayoritas berdenominasi rupiah, sehingga risiko kurs terhadap stok utang menurun. Sebesar 11,88% lainnya berupa pinjaman luar negeri (campuran bilateral-Jepang, Tiongkok-dan multilateral). Namun, di sisi lain, pernyataan BI mengenai potensi “crowding out” mesti diindahkan. Per akhir Juli 2025, investor domestik memegang 85,4%; porsi BI mencapai 24,2% dan perbankan 20% dari SBN yang dapat diperdagangkan. Bila bank menjadi pembeli marginal saat penerbitan meningkat, term premium (proksi selisih yield SBN 10Y (6,44%) terhadap BI-Rate (5,25%) cenderung melebar dan mengakibatkan penyaluran kredit swasta berisiko tertahan. Dengan kata lain, struktur yang aman dari sisi valas tidak otomatis murah dari sisi biaya kesempatan perekonomian.
Kondisi Fiskal
BPS merilis pertumbuhan ekonomi tahun-ke-tahun 5,12% untuk triwulan II 2025. Posisi fiskal Indonesia relatif kuat untuk mendukung target penurunan defisit anggaran dari 2,8% PDB (Rp 522 triliun) menjadi 2,5% pada 2026. Laju pertumbuhan ini memberikan dorongan pada basis pajak, terutama dari PPN akibat konsumsi domestik yang stabil, serta PPh badan dari sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa.
Di sisi hubungan pusat–daerah, penataan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan perlu dijalankan dengan hati-hati. Tanpa pengaman pada belanja wajib (pendidikan, kesehatan) dan capex daerah, penyesuaian TKD berisiko menekan layanan dasar serta menunda proyek kecil ber-ROI tinggi. Hal ini dapat menghambat belanja daerah dan pertumbuhan lokal.
Outlook terbaru menunjukkan disiplin fiskal menipis: keseimbangan primer 2025 direvisi ke defisit Rp110 triliun (dalam UU APBN defisit Rp63 triliun), memburuk sekitar Rp90 triliun dibanding realisasi 2024. Pemicu utamanya adalah revisi penurunan pendapatan sementara belanja tetap tinggi, sehingga stabilisasi utang makin bergantung pada keseimbangan primer dan pada selisih antara bunga utang dan laju ekonomi ke depan.
Kualitas belanja menentukan apakah utang menjadi akselerator pertumbuhan atau sekadar beban yang berulang. Kajian Bank Dunia menyatakan jika hanya 55% utang Indonesia yang terkait dengan sektor produktif. Jika hanya sebesar itu utang yang produktif, artinya “golden rule of public finance” kita, meminjam untuk investasi, bukan untuk konsumsi, belum sepenuhnya tegak. Proyek yang didanai utang harus mampu menurunkan biaya logistik, memperluas basis pajak di masa depan, dan memperkuat kapasitas ekspor agar utang tetap menjadi akselerator pertumbuhan.
Di lain sisi, faktor eksternal tahun ini kurang bersahabat. Selama suku bunga The Fed dipertahankan pada rentang 4,25-4,50 persen dan ekspektasi pelonggaran belum kuat, biaya refinancing pinjaman valas cenderung lebih mahal. Pelemahan rupiah melewati Rp16,000 per dolar AS akan menekan pembayaran valas dan menyalakan lampu kuning pada imported inflation. Dalam kondisi seperti ini, disiplin fiskal bukan sekadar preferensi, melainkan asuransi agar tekanan eksternal tidak menular ke domestik. Di dalam negeri, tekanan terbesar tetap datang dari subsidi energi yang diproyeksikan sekitar Rp350 triliun pada 2025.
Institusi internasional menawarkan nada serupa. IMF mendorong penguatan tax ratio (kini sekitar 10,3% PDB) dan reformasi subsidi; Fitch mempertahankan peringkat BBB tetapi menyoroti kerentanan fiskal bila tren utang menanjak; dan BI mengingatkan efek crowding out. Pesan umum yang konsisten: kredibilitas fiskal menjadi jangkar stabilitas makro. Kredibilitas ini harus tercermin melalui rangkaian kebijakan yang bisa diaudit publik: keseimbangan primer, plafon defisit yang realistis, dan pipeline proyek yang transparan.
Rekomendasi Fiskal
Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Pertama, sisi penerimaan harus diperkuat melalui perluasan basis pajak yang nyata, bukan sekadar menaikkan tarif. Menkeu menyatakan jika Prioritas 2026 bukan tarif baru, melainkan reformasi sistem. Artinya, salah satu fokus penerimaan 2026 bertumpu pada Coretax, tetapi rollout-nya tahun ini bermasalah (gangguan layanan dan migrasi data yang belum rapi), sehingga risiko ini perlu diantisipasi dalam target penerimaan.Revisi lanjutan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga perlu benar-benar menangkap ekonomi digital dan mendorong formalisasi UMKM tanpa menimbulkan disinsetif bagi pelaku usaha. Kedua, belanja harus lebih produktif dan terukur hasilnya. Studi kelayakan independen, tolok ukur ROI ekonomi, analisis biaya-manfaat sosial, dan stage-gate yang memungkinkan proyek dihentikan bila tidak memenuhi capaian. Ketiga, manajemen utang aktif. Di lingkungan suku bunga tinggi, memperpanjang durasi penerbitan SBN (termasuk seri 20-30 tahun), memanfaatkan basis investor domestik (ritel, dana pensiun, asuransi) dan regional (sukuk yang menarik investor kawasan). Keempat, subsidi energi harus ditata ulang menjadi bantuan yang tepat sasaran dan berjangka waktu jelas. Alihkan dari subsidi harga yang menyebar ke subsidi orang yang ditarget (berbasis DTKS yang sudah dibersihkan).
Risiko fiskal 2025 harus dikelola melalui skenario yang gamblang. Dalam skenario optimistis, reformasi pajak berjalan, harga komoditas stabil, rupiah terjaga, rasio utang bisa kembali di bawah 40% PDB dalam dua-tiga tahun karena kombinasi pertumbuhan riil di atas 5 persen, inflasi yang terjaga, dan keseimbangan primer yang bergerak menuju nol lalu surplus tipis. Di skenario pesimistis, perlambatan global, penguatan dolar, dan koreksi harga komoditas, rasio dapat menembus 43 persen dengan tekanan pada rupiah. Perbedaan kedua jalur ini terutama ditentukan oleh tiga poin: disiplin belanja, efektivitas penerimaan, dan kredibilitas komunikasi pemerintah.